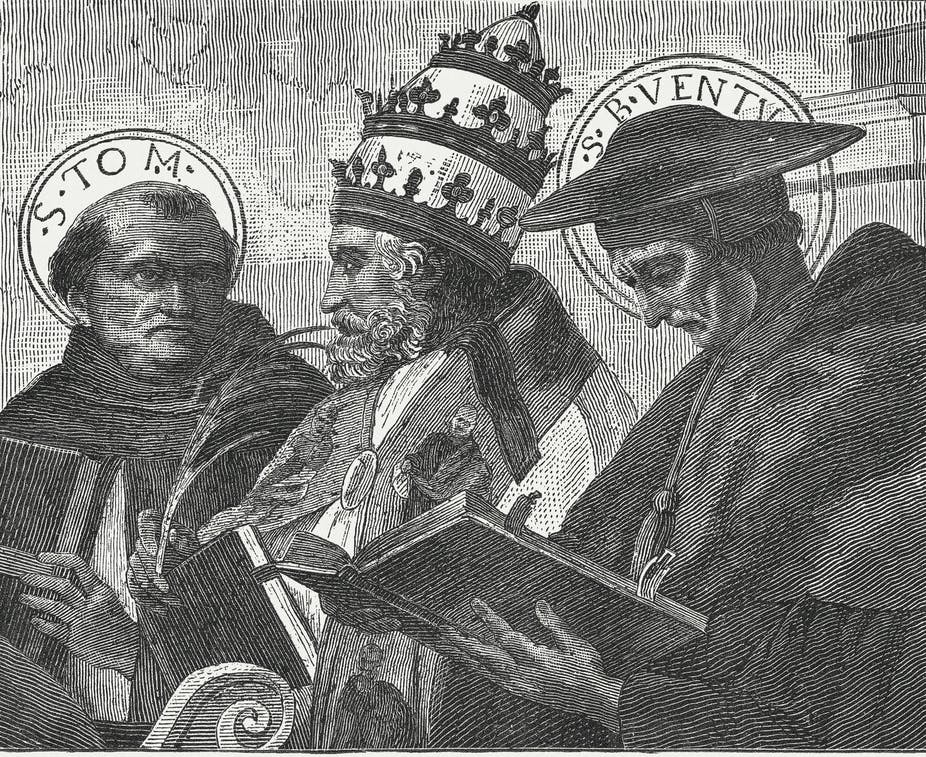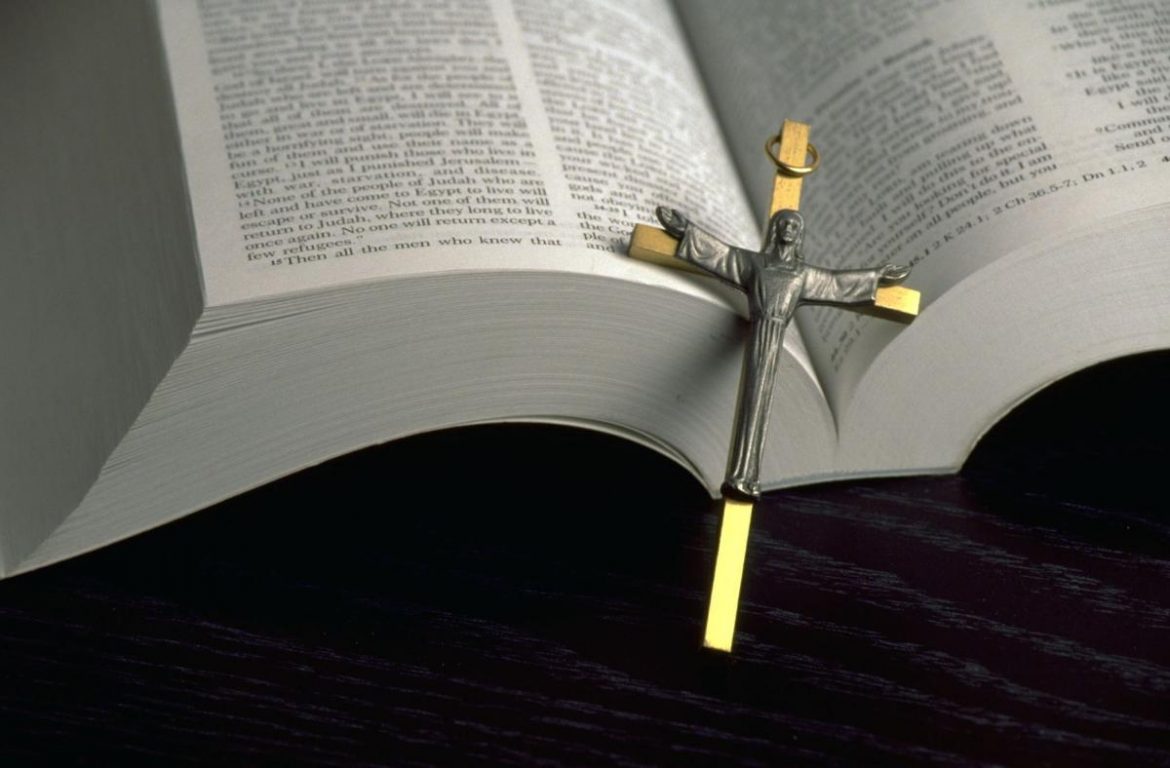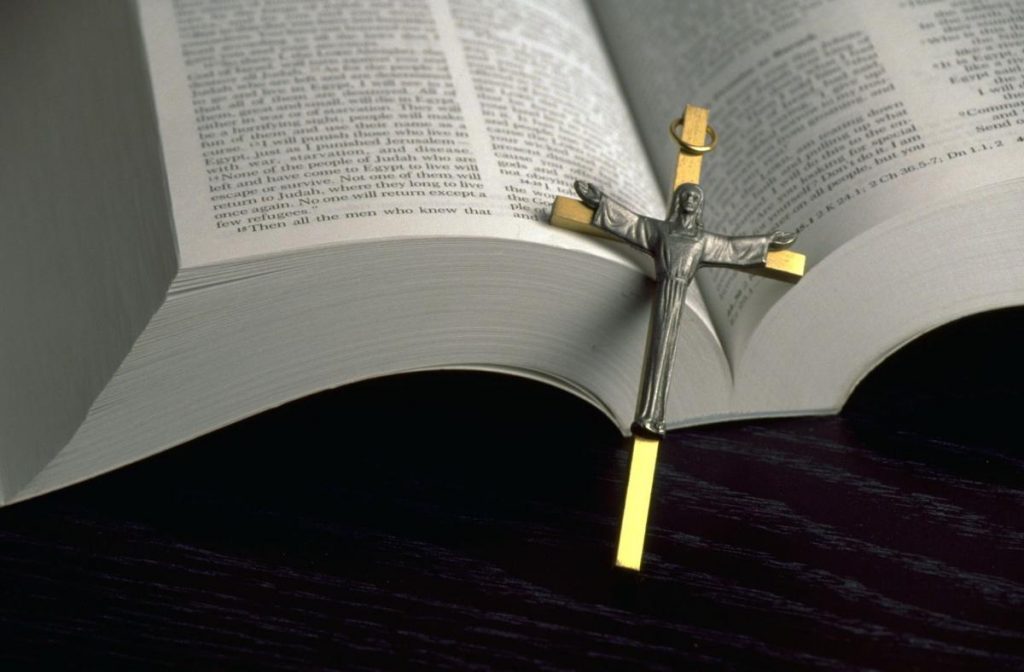Thomas Aquinas Ajarkan Harapan di Saat-saat Putus Asa – Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika sangat khawatir dengan keadaan demokrasi AS.
Satu survei dari Januari 2022 menemukan bahwa 64% orang Amerika percaya bahwa demokrasi AS “dalam krisis dan berisiko gagal.”

Baik Partai Republik maupun Demokrat menegaskan keprihatinan ini, tetapi mereka memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang apa yang sebenarnya ada dalam krisis dan siapa yang bertanggung jawab. hari88
Yang paling penting, jajak pendapat telah berulang kali menemukan bahwa mayoritas Partai Republik – puluhan juta orang Amerika – terus percaya kebohongan bahwa pemilu 2020 dicuri.
Bagi orang-orang Amerika yang tahu bahwa itu tidak benar, komitmen yang mengakar dari rekan-rekan Amerika mereka untuk kebohongan tidak diragukan lagi memperburuk kekhawatiran mereka.
Bagaimana Anda berdebat dengan seseorang yang berkomitmen untuk berbohong?
Tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang harus dilakukan, mengingat begitu banyak orang Amerika – termasuk saya sendiri – takut akan kelangsungan hidup demokrasi kita.
Sebagai seorang sarjana yang meneliti nilai-nilai demokrasi, saya telah menghabiskan waktu dengan karya Thomas Aquinas, seorang biarawan Dominikan yang hidup pada abad ke-13.
Kata-kata Aquinas relevan dengan waktu di mana kita menemukan diri kita sendiri. Di atas segalanya, dia menunjukkan apa artinya berharap.
Harapan sebagai kebajikan teologis
Aquinas secara luas dianggap sebagai teolog Katolik tunggal yang paling penting. Tubuhnya yang besar bekerja berbicara kepada hampir setiap aspek iman Kristen.
Yang paling penting, mungkin, Aquinas bersikeras bahwa akal dan wahyu adalah bentuk pengetahuan yang terpisah tetapi saling melengkapi.
Dia berargumen bahwa karena keduanya pada akhirnya berasal dari Tuhan, mereka tidak dapat bertentangan.
Dengan demikian, Aquinas juga merupakan salah satu pemikir pertama yang mendamaikan karya filsuf Yunani kuno Aristoteles dengan agama Kristen.
Aristoteles berpendapat bahwa etika pada prinsipnya berkaitan dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.
Bagi Aristoteles, orang yang benar-benar etis juga merupakan orang yang benar-benar luar biasa.
Aquinas menerima pemahaman ini. Tetapi dia juga berpendapat bahwa interpretasi Aristoteles tentang etika tidak lengkap dan tidak sempurna.
Aquinas mengatakan bahwa etika juga harus memasukkan nilai-nilai teologis iman, harapan dan amal.
Kebajikan-kebajikan ini, menurut Aquinas, datang kepada kita bukan dari akal tapi dari anugerah.
Mereka adalah karunia dari Tuhan yang berfungsi untuk mengarahkan orang-orang menuju keselamatan mereka.
Menurut teolog, mereka memungkinkan manusia untuk mencapai dimensi kebahagiaan dan keunggulan yang tidak dapat mereka capai sebaliknya.
Aristoteles mendefinisikan kebajikan sebagai “perantara antara dua sifat buruk, yang bergantung pada kelebihan dan yang bergantung pada cacat.”
Jadi, misalnya, Aristoteles mengatakan bahwa keberanian ditemukan di antara kecerobohan – kelebihan keberanian – di satu sisi dan kepengecutan, kekurangannya, di sisi lain.
Memutuskan bagaimana menjadi berani tidak pernah sederhana dan tergantung secara dramatis pada keadaan, tetapi keberanian akan selalu ditemukan di antara ekstrem ini.
Aquinas mengikuti konsep kebajikan ini, dan dia berpendapat bahwa kebajikan teologis dari harapan cocok dengan polanya.
Menurutnya, itu terletak di antara dua sifat buruk: Prasangka adalah kelebihan harapan, sedangkan keputusasaan adalah kekurangannya.
Praduga adalah keyakinan mudah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Orang yang menduga-duga berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak dia berdosa, seperti yang dicatat Aquinas, “Tuhan tidak akan menghukumnya atau mengeluarkannya dari kemuliaan.”
Keputusasaan adalah kebalikannya. Itu berarti orang berdosa percaya bahwa dia telah jatuh begitu jauh dari Tuhan sehingga dia tidak memiliki kemungkinan keselamatan.
Pertanyaan tentang keselamatan adalah satu hal, sedangkan kondisi demokrasi Amerika sepenuhnya lain.
Namun demikian, ada contoh banyak orang Amerika yang menanggapi krisis demokrasi saat ini dengan sifat buruk praduga dan keputusasaan yang sama.
Praduga dan keputusasaan demokratis
Dalam krisis demokrasi saat ini, anggapan muncul sebagai optimisme yang samar-samar bahwa demokrasi Amerika telah selamat dari banyak krisis dan bahwa ini hanyalah satu lagi.
Banyak orang Amerika percaya bahwa krisis saat ini adalah masalah yang harus ditangani oleh mereka yang berkuasa; bersiul melewati kuburan, mereka tidak melihat alasan untuk mengubah perilaku mereka sendiri.
Ilmuwan politik Sam Rosenfeld mencatat bahwa meskipun ada perasaan krisis, “perilaku memilih tidak berubah sebagai tanggapan; itu menunjukkan stabilitas dan kontinuitas yang luar biasa dengan pola yang ditetapkan pada awal abad ini.”
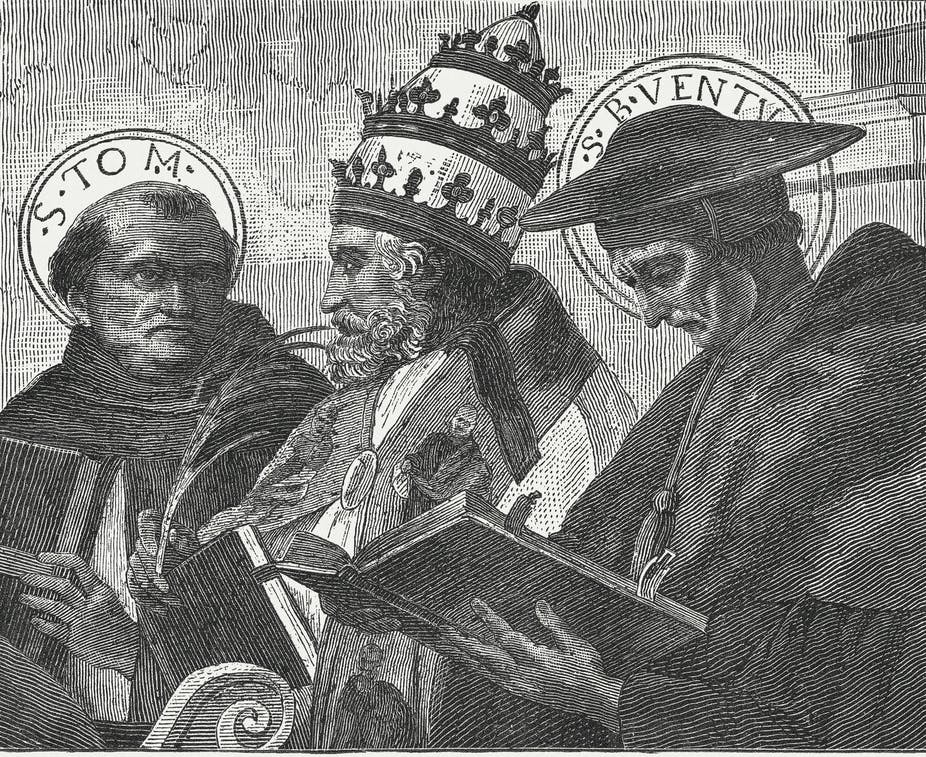
Keputusasaan bahkan lebih terlihat. Sebagian besar orang Amerika telah mengungkapkan setidaknya perasaan putus asa sementara seputar perubahan iklim dan pandemi yang tampaknya tidak pernah berakhir, dan juga tentang demokrasi kita.
Dan tidak diragukan lagi bahwa semua krisis ini terjadi secara bersamaan hanya menambah perasaan bahwa mereka berada di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya.
Tapi bagi Aquinas, harapan bukan sekadar jalan tengah di antara dua sifat buruk ini; itu juga merupakan respons yang lebih realistis terhadap kondisi kita.